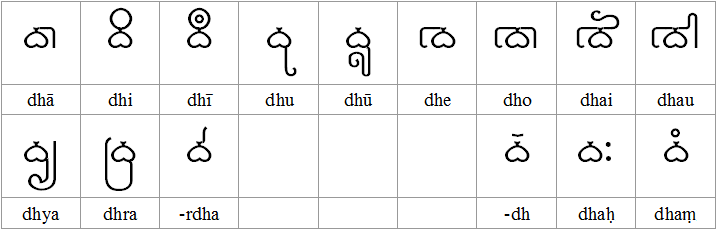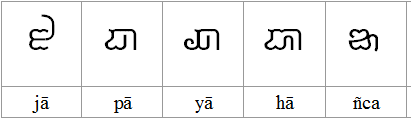|
| Kerabat dan Nenek moyang Aksara Jawa |
|
|
Belajar Menulis Aksara Jawa:
Memahami Asal Huruf Jawa Asli
Aksara Devanagari
 |
| Kaligrafi Devanagari |
Aksara Devanāgarī atau
aksara Dewanagari (dari bahasa Sanskerta: "kota dewa") adalah sebuah jenis
aksara yang berasal dari
India bagian utara. Aksara ini muncul dari
aksara Brahmi dan mulai dipergunakan pada
abad ke-11. Aksara Dewanagari ini merupakan turunan dari Aksara Brahmi Kuno lembah
Hindhus yang juga merupakan turunan dari Aksara Phoenecia di sekitar
Palestina. Aksara ini terutama dipergunakan untuk menuliskan
bahasa Hindi dan
bahasa Sanskerta.
Namun perlu diberi sedikit catatan di sini, bahasa Sanskerta tidak
mutlak ditulis menggunakan aksara ini tetapi juga dengan banyak aksara
lainnya, antara lain aksara-
aksara Nusantara.
Aksara Dewanagari ditulis dari kiri dan sedikit condong ke kanan akibat pengaruh gaya tulis Arab. Selain itu, seperti aksara India Utara pada umumnya, ditulis dengan menggunakan garis di atas sebagai tempat bergantung huruf-hurufnya dan pemisah kata demi kata.
Daftar aksara
Vokal (Swara)
| Aksara |
Bentuknya dengan konsonan [k] |
Alihaksara |
IPA |
Contoh dalam bahasa Indonesia |
| अ |
प (mandiri) |
a |
a |
kabel |
| आ |
पा |
ā |
ɑ |
karton |
| इ |
पि |
i |
ɪ |
|
| ई |
पी |
ī |
i |
istri |
| उ |
पु |
u |
ʊ |
kucing |
| ऊ |
पू |
ū |
u |
kurma |
| ऋ |
पृ |
ṛ |
r̩ |
berkat |
| ॠ |
पॄ |
ṝ |
rː̩ |
|
| ऌ |
पॢ |
ḷ |
l ̩ |
|
| ॡ |
पॣ |
ḹ |
lː̩ |
|
| ऍ |
पॅ |
candra e |
|
|
| ऎ |
पॆ |
e pendek |
|
|
| ए |
पे |
e |
e |
lélé |
| ऐ |
पै |
ai |
ai atau ɛ |
ramai |
| ऑ |
पॉ |
o (terbuka) |
|
|
| ऒ |
पॊ |
|
|
|
| ओ |
पो |
o (tertutup) |
aʊ atau o |
sop |
| औ |
पौ |
au (panjang) |
ɔ |
rantau |
Vokal : beberapa kasus dengan र
| Vokal |
Bentuk sandhangan dengan aksara [r] |
| उ |
रु |
| ऊ |
रू |
Tanda-tanda diakritik lainnya
| Huruf |
Nama |
Fungsi |
| प् |
wirāma (विराम) |
juga disebut halant (हलन्त) dalam bahasa Hindi, "membunuh" vokal pada konsonan yang menyangganya |
| एँ |
candrabindu (चन्द्रबिन्दु) |
menyengaukan vokal |
| पं |
anuswāra (अनुस्वार) |
menyengaukan vokal atau memberikan konsonan sengau setelah vokal (biasanya [n]) |
| एः |
wisarga (विसर्ग) |
[h] pada posisi akhir |
| फ़ |
nukta (नुक्ता) |
digunakan untuk kata-kata pinjaman |
| एऽ |
awagraha (अवग्रह) |
untuk memperpanjang vokal |
Konsonan (Wyañjana)
| Aksara |
Alihaksara |
IPA |
Contoh dalam bahasa Indonesia |
| क |
k |
k |
katak |
| ख |
kh |
kh |
|
| ग |
g |
g |
garing |
| घ |
gh |
gɦ |
|
| ङ |
ṅ |
ŋ |
ngawur |
| च |
c |
ʧ |
cacing |
| छ |
ch |
ʧh |
|
| ज |
j |
ʤ |
jagung |
| झ |
jh |
ʤɦ |
|
| ञ |
ñ |
ɲ |
nyanyi |
| ट |
ṭ (retrofleks) |
ʈ |
t dalam bahasa Bali |
| ठ |
ṭh (retrofleks) |
ʈh |
|
| ड |
ḍ (retrofleks) |
ɖ |
|
| ढ |
ḍh (retrofleks) |
ɖɦ |
dh dalam bahasa Jawa |
| ण |
ṇ (retrofleks) |
ɳ |
|
| त |
t |
t̪ |
tari |
| थ |
th |
t̪h |
|
| द |
d |
d̪ |
dansah |
| ध |
dh |
d̪ɦ |
|
| न |
n |
n |
nama |
| प |
p |
p |
papa |
| फ |
ph |
ph |
|
| ब |
b |
b |
balon |
| भ |
bh |
bɦ |
|
| म |
m |
m |
mama |
| य |
y |
j |
yakuza |
| र |
r |
ɾ |
|
| ल |
l |
l |
laku |
| ळ |
y (hanya dalam bahasa Marathi) |
j |
|
| व |
v |
v |
wahana |
| श |
ś (sy) |
ɕ |
syarat |
| ष |
ṣ (retrofleks) |
ʂ |
surat |
| स |
s |
s |
satu |
| ह |
h |
h |
|
| क़ |
q (untuk kata-kata pinjaman dari bahasa Arab) |
q |
Arab qalbu |
| ख़ |
x |
x |
kh (untuk kata-kata pinjaman dari bahasa Arab) |
| ग़ |
ġ (r uvular) |
ʀ |
|
| ज़ |
z (untuk kata-kata pinjaman Persia dan Arab) |
z |
zéro |
| ड़ |
ṛ (retrofleks) |
ɽ |
|
| ढ़ |
ṛh (retrofleks) |
ɽɦ |
|
| फ़ |
f (untuk kata-kata pinjaman asing) |
f |
foto |
Bilangan
| Huruf |
Alihaksara |
| ० |
0 |
| १ |
1 |
| २ |
2 |
| ३ |
3 |
| ४ |
4 |
| ५ |
5 |
| ६ |
6 |
| ७ |
7 |
| ८ |
8 |
| ९ |
9 |
Simbol lain
| Aksara |
Nama |
Fungsi |
| । |
danda (डण्डा) |
. (akhir kalimat) |
| ॥ |
double danda |
penanda akhir sebuah rima pada puisi |
| ॐ |
Ôm |
simbol sakral Hindu |
Aksara yan Lain
- श्र = shra
- ह्न = hna
- ह्म = hma
- ह्ल = hla
- ह्य = hya
- क्त = kta
Aksara Pallawa

Aksara Bangsa Dravidian
Aksara Pallawa atau kadangkala ditulis sebagai
Pallava adalah sebuah aksara yang berasal dari
India bagian selatan. Aksara ini sangat penting untuk sejarah di Indonesia karena aksara ini merupakan aksara dari mana
aksara-aksara Nusantara diturunkan.
Di Nusantara bukti terawal adalah
Prasasti Mulawarman di
Kutai,
Kalimantan Timur yang berasal dari
abad ke-5 Masehi. Bukti tulisan terawal yang ada di
Jawa Barat dan sekaligus
pulau Jawa, yaitu
Prasasti Tarumanagara yang berasal dari pertengahan abad ke-5, juga ditulis menggunakan aksara Pallawa.
Nama aksara ini berasal dari Dinasti Pallava yang pernah berkuasa di selatan India antara
abad ke-4 sampai
abad ke-9 Masehi. Dinasti Pallava adalah sebuah dinasti yang berada di India bagian selatan dan merupakan Dinasti bangsa Dravidian.
Tidak seperti Aksara Dewanagari, Aksara Pallawa tidak menggunakan garis atas sebagai pemisah kata demi kata dan merupakan sistem penulisan tanpa spasi atau kontinu.
Aksara ini merupakan leluhur dari aksara:
- Mon – Burma
- Kawi –
Jawa, Bali, Sunda, Bugis, dll )keluarga aksara di Indonesia, Filipina, Kalimantan)
- Lanna, Tham (Thailand)
- Khom (Thailand)
- Khmer – Kamboja
- Thai-Thailand and Lao-Laos
- Tai Lue dan aksara bahasa Tai lainnya (Burma, Cina Selatan, Thailand,
Vietnam)
- Cham (Vietnam)
Konsonan
Aksara Swara dan sandhangan
Variasi pada bentuk sandhangan
 |
| Sandhangan yang mirip dengan Aksara Jawa |
Bentuk kombinasi khusus
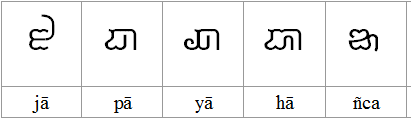
Aksara Kawi
 |
| Aksara Kawi jenis Kuadrat |
Aksara Kawi (
bahasa Sanskerta:
kavi yang berarti 'pujangga')
adalah aksara Brahmi historis yang pernah digunakan di wilayah maritim
Asia tenggara sekitar abad 8 hingga 16 Masehi. Aksara ini terutama
digunakan di wilayah Jawa dan Bali,
Indonesia, namun beberapa prasasti bertulis Kawi telah ditemukan sampai sejauh
Filipina. Aksara ini digunakan untuk menulis bahasa Sanskerta dan
Jawa kuno.
Aksara Kawi pada perkembangannya menjadi nenek moyang dari
aksara-aksara tradisional Indonesia seperti aksara Jawa, Bali, Sunda, dn
lain-lain
.
Aksara ini ditulis tanpa spasi (
scriptio continua) seperti aksara Pallawa.
Aksara Kawi memiliki sekitar 47 huruf, namun terdapat sejumlah huruf
yang bentuk dan penggunaannya tidak diketahui pasti karena sedikitnya
contoh yang ditemukan dalam prasasti bertulis Kawi.
Aksara Kawi memiliki bentuk subskrip huruf yang digunakan untuk menulis tumpukan konsonan, setara dengan
pasangan dalam
aksara Jawa dan
pangangge dalam
aksara Bali. Subskrif tersebut merupakan temuan asli peradaban lokal di Nusantara.
Namun beberapa inskripsi Aksara Kawi tidak menggunakan pasangan dalam
penulisannya atau meniru penggunaan aksara Pallawa dan Dewanagari yang hanya menggunakan Virama (pangkon), seperti prasasti pada Candi Sukuh Ngargoyoso, Karanganyar,
Jawa Tengah.
 |
| 'Air telaga jernih bagaikan langit'. Cuplikan dari Kakawin Ramayana, 16.31, (Bhramara wilasita) |
Perbedaan terpenting antara Aksara Pallawa dengan Aksara Jawa Kuno antara lain adalah :
- Aksara Jawa Kuno memiliki vokal e pepet dan vokal e pepet panjang,
sedangkan Aksara Pallawa tidak memiliki vokal e pepet atau vokal e pepet
panjang.
- Aksara Jawa Kuno cukup sering menggunakan tanda virama untuk
menghilangkan vokal pada huruf konsonan, sedangkan Aksara Pallawa
biasanya hanya menggunakan virama di akhir kalimat atau di akhir bait.
- Aksara Jawa Kuno memiliki bentuk karakter berbeda dibanding Aksara Pallawa, walaupun beberapa huruf masih ada kemiripan.
Aksara Jawa Lengkap (Asli)
Aksara Jawa asli adalah aksara Jawa yang jumlah aksara dan bentuk serta penggunaanya sesuai dengan Aksara Dewanagari dan Pallawa serta menganut kaidah penulisan sandhi pada bahsa Sansekerta yang dibuat oleh Empu Panini pada sekitar tahun 500 Sebelum Masehi.
Aksara ini secara umum digunakan secara signifikan sejak jaman Kerajaan Hindhu-Budha akhir sebelum runtuhnya kerajaan Majapahit. Namun penggunaannya hanya berkisar pada golongan terpelajar saja dari darah bangsawan maupun para pendheta karena keharusan akan mematuhi semua sandhi (aturan) dari bahasa Sansekerta.
Karena tidak banyak yang mengetahui kaidah-kaidah tersebut serta untuk mempermudah komunikasi dengan rakyat biasa yang kurang terpelajar, maka aksara jawa lama-kelamaan mulai tidak mengikuti kaidah Sandhi Sansekerta sedikit demi sedikit terutama sejak adanya penyederhanaan aksara Jawa yang diputuskan dengan Wawaton Sriwedari oleh para penggunanya pada saat pertemuan di Surakarta.
Dampaknya, penggunaan aksara Jawa pada jaman Penjajahan Hindia Belanda menjadi sangat signifikan hingga ke tiap-tiap pelosok yang dapat terjangkau. Aksara Jawa menjadi lebih mudah bagi mereka yang kurang terpelajar saat itu sehingga penggunaannya lebih luas untuk sarana komunikasi.
Namun, tentu saja hal ini berdampak buruk juga bagi peradaban Jawa yang menjadi mundur dikarenakan penggunaan aksara yang kompleks menjadi sederhana bahkan dikalangan terpelajar saat itu. Sehingga para ilmuwan bahasa Belanda mulai mencari kembali penggunaan aksara Jawa yang sebelumnya bersama beberapa kalangan terpelajar di Jawa. Akhirnya, mereka dapat mengkonfirmasi penggunaan aksara Jawa yang asli setelah adanya pelbagai temuan prasasti dibantu referensi lontar dari Bali yang masih disalin sejak jaman kerajaan jaman Hindhu-Budha. Penelitian ini salah satunya dijadikan sebuah buku yang singkat walau tentu ada sedikit-banyak kekurangan yang perlu dicari dalam penggunaan naskah kuno,
Buku Serat Mardi Kawi dan
Buku Niti Aksara Jawa. Karena itulah seyogyanya kita kembali menggunakan aksara Jawa yang asli seperti yang masih terjaga dalam budaya penulisan di Bali.
Sumber:
1. Wikipedia
2. Google gambar
Selanjutnya: